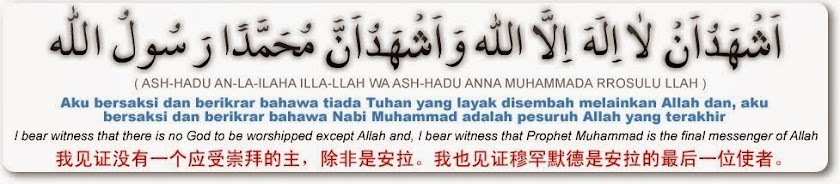Di akhir zaman ini, wa bil khusus di negeri ini bertaburan yang namanya Motivator, Trainer, Pembicara, Ustadz, Da’i, Guru, Mursyid, Konsultan, Therapist, Kyai, Syekh, Habib, Penulis Best Seller, dan lain sebagainya. Tapi uniknya, akhlak penduduk di negeri ini “sepertinya” malah kian terpuruk ya. Why?
Dalam pengamatan saya yang rendah ini, jika tujuan seseorang berbagi ilmu atau mencari ilmu adalah penghasilan, uang, atau dunia, maka ketahuilah bahwa “uang” itu energinya rendah sedangkan ilmu itu energinya sangat tinggi. Sehingga jika tujuan kita adalah uang maka kita tak akan pernah sampai kepada ilmu tersebut, apalagi sebuah ilmu yang dapat membentuk karakter dan di amalkan di kehidupan sehari-hari, hmm bagaikan asap jauh dari panggangnya.
Sehingga perlu disadari bahwa“uang” bisa menjadi hijab (penghalang) terbesar antara ilmu dan amal, antara hidayah dan kehidupan nyata. Uang bertambah, ilmu bertambah, tapi amal dan hidayah menurun drastis di kehidupan. Na’udzubillahi min dzaalik.
Nah, menurut Anda, untuk apa sih ilmu itu? Apakah untuk diamalkan, diajarkan, didebatkan, disombongkan, diadukuatkan, dipamerkan, atau diperjualbelikan? Apakah ilmu itu sebuah komoditas atau sebuah alat yang mendasar yang tidak boleh diperjualbelikan?
“Barang siapa yang belajar suatu ilmu yang seharusnya dilakukan dengan ikhlas, tetapi dia menuntutnya demi mencari keuntungan dunia darinya, maka dia tidak akan bisa mencium baunya syurga pada hari akhir” (H.R. Abu Daud).
Sahabatku yang berhati lapang, kini sebagian dunia pendidikan pun lebih mirip membangun bisnis perdagangan dibandingkan pembangunan karakter anak bangsa. Kompetensi yang dimiliki guru pun didagangkan dan ditukar dengan sejumlah uang (SPP) yang dibayarkan oleh orang tua murid di setiap bulannya.
Tak heran bila banyak guru yang kehilangan “magnet” digugu dan ditiru , bahkan justru banyak murid yang culangung alias kurang ajar kepada para gurunya karena mereka menganggap “guwa kan sekolah di sini bayar muahhaal ”.
Nah, karena iklim yang terlanjur dibangun di dunia pendidikan kita adalah “menuntut ilmu sebagai sarana mencari nafkah” , baik untuk guru atau untuk murid-muridnya, maka ketika pemerintah mengadakan program “Pendidikan Gratis” maknanya justru menjadi “Pendidikan tidak Berkualitas”.
Padahal, dalam sejarah pemerintah Islam, pendidikan itu gratis, namun demikian para Guru/Ustadz/Ulama nya adalah orang-orang yang sangat dihormati. Hal ini terjadi karena orientasi guru dan murid sama, yaitu menuntut dan mengajarkan ilmu itu untuk membangun karakter/akhlak dan akidah demi keselamatan di dunia dan akhirat, dan bukan untuk mencari nafkah semata.
Sahabatku, coba perhatikan fenomena tawuran di negeri ini, tawuran justru banyak terjadi di dunia pendidikan. Selain tawuran masih banyak kejahatan yang terjadi di dunia pendidikan, seperti : nyontek berjama’ah, zina antar pelajar, zina antar guru dan murid, penyebaran film porno, jaringan narkoba, dan korupsi yang sudah dianggap wajar oleh sebagian guru.
Yang uniknya adalah orang tua murid pun kadang lebih sedih bila anaknya tidak bisa matematika dibandingkan tidak bisa jujur, tidak bisa berhenti di kala lampu merah menyala di lalu lintas, dan tidak bisa ngantri dengan benar .
Saking sibuknya sebagian para guru, murid, dan ortu murid dalam hal mengejar target, nilai, pengakuan, penghargaan, kompetensi, dan reputasi sekolah, maka akhlak dan karakter anak bangsa pun dikorbankan hidup-hidup.
Sebagian dari mereka berpendapat : lebih baik nyontek berjama’ah ketika UN daripada reputasi sekolah hancur karena nilai UN akumulatif sekolah tidak sesuai target. Padahal jelas-jelas pesan Nabi itu “Mencari Ilmu” dan bukan “Mencari Nilai”. Biasanya, mencari ilmu itu untuk diamalkan, sedangkan mencari nilai itu untuk dipamerkan, right ?
Sahabatku, “tholabul ‘ilmi” sering diartikan “mencari ilmu”, dan itu benar. Tholabu berasal dari kata tholaba yang artinya menuntut atau “meminta”.
Sehingga hakikat “tholabul ‘ilmi” adalah “mencari ilmu dengan carameminta kepada yang memiliki ilmu” dan bukan “mencari ilmu dengan cara membeli kepada yang memiliki ilmu”. Adapun memberi ilmu kepada yang memintanya adalah kewajiban, tentu saja disesuaikan dengan kondisinya.
Yang penting adalah jangan sampai kita tidak jadi memberikan ilmu hanya lantaran si peminta ilmu tidak sanggup membayar atau membeli ilmu yang kita miliki sesuai dengan harga yang kita tetapkan. Padahal ilmu “rahasia kehidupan” itu sangatlah mahal, sehingga bisa jadi sebesar apapun harga yang kita tetapkan maka kita telah “merendahkan ilmu yang kita miliki”.
Allaahu Akbar, nah jika seorang pembicara ketika ia berbicara menyampaikan ilmunya lalu yang terbayang di otaknya adalah “uang atau bayaran tertentu” maka bayangan itu bisa menutup vibrasi / energi ruhani spiritual yang seharusnya terpancar dari jiwa si pembicara kepada para audiennya.
Nah, bagaimana baiknya? Indahnya sih bila suatu saat dalam dunia “pendidikan”, “training spiritual”, apalagi “ceramah agama”, tidak ada lagi istilah “bayar”, bahkan kalau perlu tidak ada lagi istilah “gratis” , tapi sama-sama sadar dan saling mengerti antara pembicara, pendidik dengan para pendengar dan murid-muridnya.
Misalkan, pembicara memberikan ilmunya karena Allah, dan si pendengar pun mendapatkan ilmu dan hidayah dari Allah, dan bukan dari si pembicara. Pembicara hanyalah washilah di dunia fisik saja.
Setelah si pendengar mendapatkan ilmu dan hidayah dari Allah, maka si pendengar dengan rela hati memberikan hadiah berupa apa saja yang baik kepada si pembicara, memberikannya karena Allah dan bukan karena ilmu si pembicara. Diberikan sesuai kemampuan, dengan membesarkan tekad dan niat di jalan kebaikan, dan besarnya tidak ditentukan oleh si pembicara. Insya Allah berkah. Alhamdulillah.
Wallahu a’lam